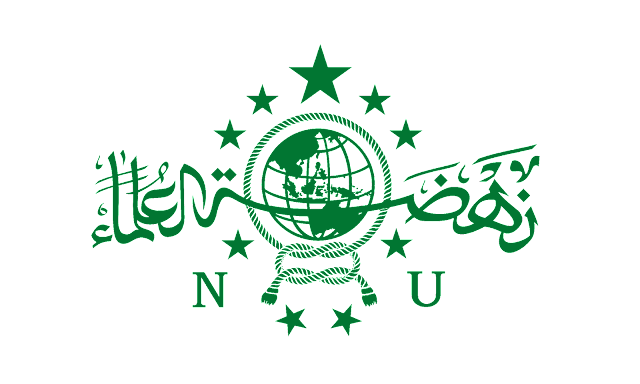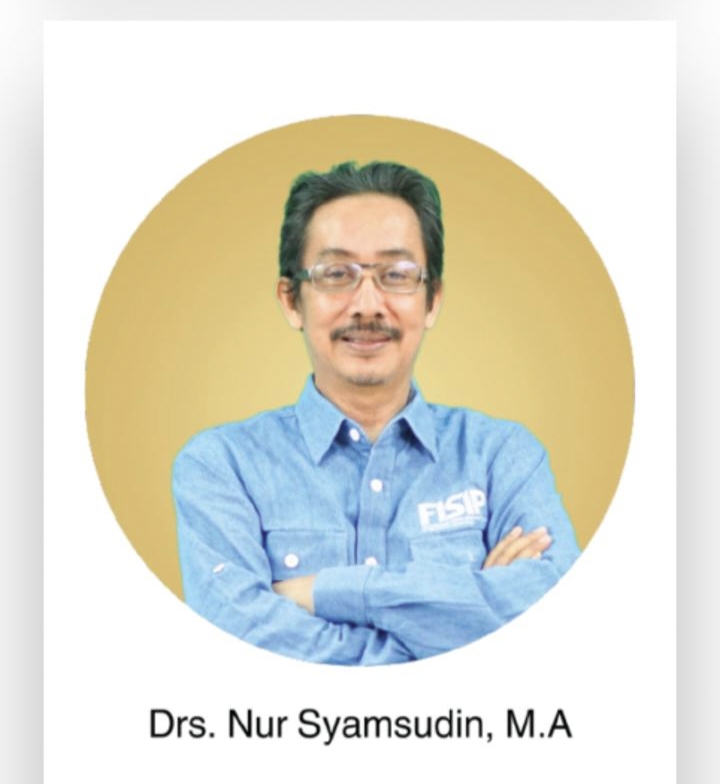Oleh: Arina Rohmah, S.Psi.I.
(Sekretaris Yayasan Azzahro Penggaron Kidul Pedurungan Semarang)
Nama KH Thohir tidak sekadar tertulis di sebuah papan jalan di Penggaron, Semarang. Ia adalah simbol perjuangan, spiritualitas, dan keteladanan seorang ulama Jawa yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan realitas masyarakat zamannya. Dari rumah yang pernah dijadikan markas pejuang kemerdekaan hingga pondok pesantren yang berdiri hingga kini, warisan KH Thohir tetap hidup dan tumbuh di jantung masyarakat Semarang Timur.
Menelusuri Akar Spiritual dan Genealogi Intelektual
KH Thohir lahir di Dukuh Teguhan, Desa Wringinjajar, Mranggen, Demak, dari pasangan Mbah Mertojoyo. Sejak belia, ia menunjukkan ketertarikan mendalam pada ilmu agama. Perjalanan intelektualnya melintasi berbagai pesantren di Nusantara, hingga akhirnya menuntut ilmu ke tanah suci Makkah. Di sana, ia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu syariah, tetapi juga memasuki dunia tasawuf dan spiritualitas Islam yang lebih dalam melalui thariqah.
Ia menikah dengan Hj. Aminah, putri dari KH Abu Naim, ulama terkemuka Penggaron yang memiliki silsilah keilmuan hingga Sunan Pandanaran. Dengan pernikahan itu, KH Thohir kemudian menetap di Penggaron dan mulai menata kehidupan dakwah, spiritual, sekaligus perjuangan kebangsaan.
Menjadi Mursyid Thariqah dan Guru Umat
Tidak semua ulama mampu menyeimbangkan peran sebagai guru lahiriah dan ruhaniah. KH Thohir adalah salah satunya. Ia mendapat ijazah dan baiat sebagai mursyid thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah dari Syekh Asro dari Makkah, yang merupakan murid langsung dari Syekh Ali Ridlo, seorang tokoh sufi besar kota Makkah pada masanya.
Di bawah bimbingannya, thariqah tidak hanya menjadi jalan spiritual semata, tetapi juga membentuk karakter muridnya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ia mendirikan pesantren Al-Muarifah, tempat di mana ilmu fiqh, tafsir, hadits, hingga tasawuf diajarkan secara integral. Di pesantren ini pula, KH Thohir menggelar suluk dan tawajuhan, terutama di bulan Rajab dan Muharram, yang diikuti para santri dan masyarakat dari berbagai daerah.

Pondok Al-Muarifah menjadi pusat penyebaran spiritualitas Islam khas Jawa: damai, membumi, dan penuh kesabaran. Salah satu karomah yang diceritakan murid-muridnya adalah kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan air wudhu dari kulah masjid. Kisah ini bukan untuk mengkultuskan pribadi, melainkan menegaskan betapa besar kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual KH Thohir.
Markas Perlawanan Rakyat: Islam dan Kemerdekaan
Tahun 1945 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Resolusi Jihad dari KH Hasyim Asy’ari menggerakkan para ulama dan santri untuk turut serta dalam perlawanan bersenjata melawan penjajah Belanda. KH Thohir tidak tinggal diam. Bersama iparnya, KH Zaeni, ia membuka rumahnya sebagai markas perjuangan.
Wilayah Penggaron, yang saat itu masih masuk Kabupaten Demak, merupakan jalur strategis menuju Kota Semarang. Tidak heran bila Penggaron menjadi titik krusial pertempuran. Rumah KH Thohir dan KH Zaeni berkali-kali diserbu tentara Belanda karena menjadi pusat koordinasi laskar pejuang. Penyerbuan itu bahkan menyebabkan rumah mereka dihancurkan total.
Salah satu peristiwa paling tragis adalah pengeboman rumah di Bugen tahun 1946. Sebanyak 74 orang pejuang yang bersembunyi di sana tewas dalam gempuran Belanda. Mereka adalah bagian dari Hizbullah dan Sabilillah, kebanyakan berasal dari Solo. Wilayah tersebut kini dinamai Jalan Syuhada, sebagai bentuk penghormatan.
KH Thohir sendiri akhirnya mengungsi ke Sedran, Bulusari, Demak. Namun tetap aktif menyokong perjuangan lewat jaringan santri dan pengikutnya. Peran ulama dalam konteks ini tidak hanya spiritual, tetapi juga politis—tanpa kehilangan esensinya sebagai pembimbing umat.
Selepas Kemerdekaan: Membangun Warisan Peradaban Islam
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, KH Thohir kembali membangun komunitas keilmuannya. Pesantren Al-Muarifah berkembang sebagai pusat pendidikan Islam yang tetap setia pada khittah ahlussunnah wal jama’ah.
Meski usia semakin menua, KH Thohir tidak berhenti membina murid dan jamaah thariqah. Ia masih rutin memimpin suluk, memberikan ijazah amalan, dan membimbing masyarakat. Tak hanya itu, ia juga membangun tradisi keilmuan keluarga yang hingga kini masih dijaga oleh keturunannya.
KH Thohir wafat pada hari Sabtu Pon, 10 Februari 1968 (11 Dzulqa’dah 1387 H). Ia dimakamkan di kompleks pemakaman Penggaron, tidah jauh dari pesantrennya. Namun, pengaruhnya tidak ikut terkubur.
Keteladanan yang Terus Mengalir: Kiprah Dzurriyah KH Thohir

Keluarga besar KH Thohir tidak hanya menjaga warisan spiritual, tapi juga mengembangkan berbagai institusi sosial dan pendidikan. Putranya, KH Masykuri, kemudian melanjutkan perjuangan dakwah dengan mengganti nama pesantren menjadi Pondok Pesantren At-Thohiriyah. Ia juga didaulat sebagai mursyid thariqah, meneruskan sanad spiritual ayahandanya. Lembaga ini kemudian diresmikan secara formal melalui pendirian Yayasan At-Thohiriyah.
KH Masykuri menikah dengan Hj. Qomariyah dari Mranggen. Keduanya membesarkan tujuh anak yang seluruhnya aktif dalam dakwah dan pendidikan.
Putra pertama, KH Yusuf Masykuri, Lc, alumni Madinah, meneruskan memimpin Yayasan at-Thohiriyyah dan sealigus meeneruskan sebagai mursyid thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah dan KBIH al-Muna. Puteri kedua, Hj. Tazkirotul Khoiroh, aktif dalam pengajian dan pendampingan dakwah ibu-ibu.
Anak ketiga, KH M Syafi’ Masykuri, SH, MH, merupakan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palu. Anak keempat, Hj. Hanifah, mantan Ketua PC Muslimat NU Kota Semarang, mendirikan Yayasan Syaroful Millah.
Anak kelima, Hj. Amalia Hamdanah, S.IP, mengelola Yayasan Azzahro dan usaha biro travel haji-umrah Azzahro. Anak keenam, Hj. Ni’matul Aliyah, S.Ag., M.S.I., kini memimpin SMA At-Thohiriyah dan menjadi tokoh pendidikan Muslimat NU Pedurungan. Sementara anak ketujuh, M Mabrur, S.Pd., menjadi guru ASN yang meneruskan dedikasi pendidikan.
Mereka adalah bukti nyata bahwa keteladanan KH Thohir tidak hanya berupa pesan verbal, tapi juga warisan nilai yang hidup dalam praktik.
Mendakwahkan Islam Moderat di Tengah Kota
Yayasan At-Thohiriyah sebgai warisan KH Thohir mendakwahkan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah yang moderat di kota Semarang yang menaungi berbagai jenjang pendidikan: dari RA, MI, SMP, SMA, hingga KBIH dan pesantren. Lembaga ini menjadi pelita pendidikan berbasis Islam moderat di Semarang Timur. Sekolah-sekolahnya meraih prestasi akademik membanggakan, bahkan SMA At-Thohiriyah pernah masuk daftar sekolah IPA terbaik di Semarang.
Bersama Yayasan At-Thohiriyah dan Majlis Taklim Rabu Sore yang masih aktif hingga kini, menjadi salah satu jantung spiritual masyarakat. Jalan KH Thohir yang kini menghubungkan Penggaron Lor dan Penggaron Kidul hingga Tlogomulyo adalah pengingat fisik atas jejak perjuangan sang ulama. Dari lokasi yang dulunya markas perjuangan, kini berdiri pesantren dan lembaga pendidikan yang terus bertumbuh.
Menghidupkan Warisan, Membangun Masa Depan
KH Thohir adalah simbol pertautan antara agama dan perjuangan, antara spiritualitas dan kebangsaan, antara tasawuf dan keadaban publik. Ia mewakili tipikal ulama Nusantara yang tidak hanya berkutat di mimbar dan kitab, tapi juga hadir di tengah-tengah gejolak sosial, politik, dan kemanusiaan.

Dalam dunia yang semakin terpolarisasi antara ekstremisme dan sekularisme, warisan KH Thohir menjadi sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan transformasi sosial tanpa harus kehilangan jati diri spiritualnya. Ia juga membuktikan bahwa pesantren bukanlah menara gading, melainkan benteng pertahanan identitas bangsa.
Menuliskan kembali sejarah KH Thohir berarti merawat ingatan kolektif, bukan sekadar nostalgia. Sebagai upaya untuk menjadikan warisan ulama tidak hanya catatan masa lalu, tetapi juga kompas masa depan.

“Ulama sejati bukan hanya menjaga ilmu, tapi juga menjaga negeri.”
— Pesan diam yang terukir dari perjalanan hidup KH Thohir.