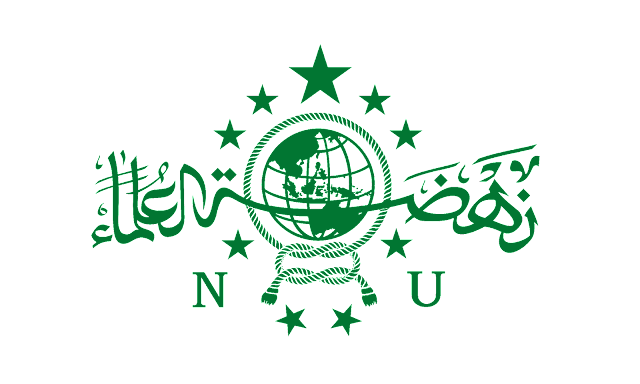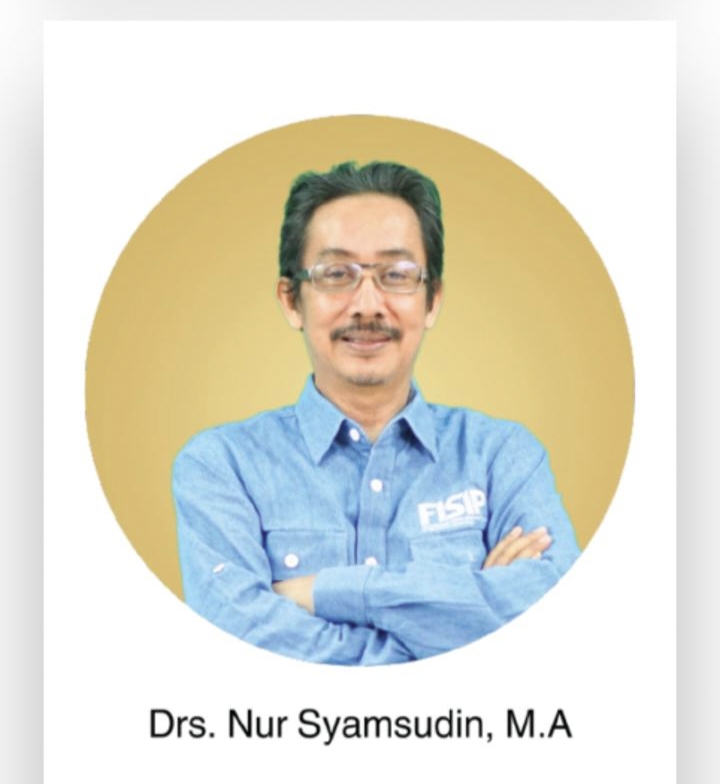Oleh M Kholidul Adib
(Sekretaris Yayasan Kota Wali Demak)
Pendahuluan
Mbah Abdul Kadir merupakan sosok santri priyayi yang ikhlas berjuang dan merakyat. Walau memiliki latar belakang keluarga priyayi tetapi rela menghabiskan hidupnya sebagai rakyat biasa. Beliau adalah putera Raden Sastrohamijoyo yang saat itu menjabat sebagai Carik Desa Wonosalam Demak yang memiliki garis keturunan Raden Kusuma keturunan Pangeran Wijil Inthik-Inthik atau Pangeran Wijil III sehingga masih dzurriyat Sunan Kalijaga.
Mbah Abdul Kadir kecil sudah menunjukkan talenta sebagai anak yang rajin belajar dan menggemari ilmu terutama ilmu agama. Masa kecil di Wonosalam beliau habiskan dengan belajar agama kepada orang tuanya. Di usia jelang remaja hingga pemuda Mbah Abdul Kadir mengenyam pendidikan di pondok pesantren Ngroto Gubug dalam waktu cukup lama sehingga menjadi lurah pondok (pesantren milik keluarga KH Hasyim Asyari, pendiri NU) dan kemudian lanjut di pesantren Girikusumo Banyumeneng Mranggen.
Setelah Mbah Abdul Kadir menikah dan berdomisili di Dukuh Gading Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak bersama Mbah Abu Mi’roj berjuang mendakwahkan agama Islam di daerah yang semula masih abangan hingga berubah menjadi kampung santri.
Latar Belakang Keluarga
Mbah Abdul Kadir lahir di Wonosalam Demak tahun 1871. Mbah Abdul Kadir adalah putera Raden Sastrohamijoyo, Carik Wonosalam Demak. Masa hidup Sastrohamijoyo sezaman dengan Pangeran Wijil V (Pemimpin Perdikan Kadilangu) yang wafat tahun 1880.
Menurut cerita Eko Wisnu Atmojo, cucu Mbah Abdul Kadir, Raden Sastrohamijoyo masih kerabat sepupu Pangeran Wijil V. Raden Sastrohamijoyo diperkirakan lahir kisaran tahun 1810-an pada saat terjadi perang Diponegoro tahun 1825-1830 beliau sudah menginjak usia muda.
Raden Sastroamijoyo menikah sebanyak 9 kali (menikah 9 kali tidak dalam satu waktu melainkan ketika ada istri meninggal atau cerai baru menikah lagi). Dari hasil menikah sebanyak 9 kali itu diketahui punya tiga anak.
Anak sulung hidup di Malaysia, anak kedua berdomisili di Batu Karangtengah Demak dan si bungsu Mbah Abdul Kadir kemudian berdomisili di Dukuh Gading Desa Candisari Kecamatan Mranggen.
Mbah Abdul Kadir adalah anak dari istri kedelapan dari Desa Ploso Karangtengah (anak lurah Ploso, desa sebelah Wonosalam). Rumah Raden Sastrohamijoyo berada tidak jauh dari lokasi sungai Tuntang di Wonosalam yang kala itu mengalirkan air ke arah kawasan Demak Kota.
Raden Sastrohamijoyo dikenal gemar tirakat dan lelaku spiritual. Beliau termasuk orang yang gemar ilmu. Saat Mbah Abdul Kadir masih kecil ibunya meninggal. Raden Sastrohamijoyo oleh anak-anaknya dinikahkaan lagi dengan istri yang kesembilan. Abdul Kadir oleh ayahnya kemudian dibawa mondok di Ngroto Gubung.
Mondok di Ngroto Gubug dan Masa Ontran-Ontran di Kadilangu
Saat Mbah Abdul Kadir sudah mondok di Ngroto Gubug, pada tanggal 11 Oktober tahun 1880 Pangeran Wijil V, pemimpin tanah perdikan Kadilangu wafat. Kemudian terjadi rebutan pemimpin Kadilangu (orang tua dulu menyebutnya ada pangeran kembar). Ontran-ontran ini terjadi selama 3 tahun (1880-1883) sehingga terjadi kekosongan atau tidak ada pemimpin resmi yang berkuasa di Kadilangu.
Situasi kala itu tambah rumit saat tiba hari raya idul adha. Sesuai adat di keluarga Kadilangu, biasanya diadakan penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yaitu baju kotang Ontokusumo dan keris Kiai Cerubuk. Namun karena ada dua pangeran yang berebut tahta, maka untuk keadilan dicarilah ahli waris yang netral dan paling sepuh.
Setelah dicari garis keturunan sepuh yang netral hasilnya jatuh pada keluarga Eyang Setro (panggilan Eyang Raden Sastrohamijoyo). Berhubung Eyang Setro sudah sepuh maka anaknya bernama Abdul Kadir yang sejak kecil sudah mondok di pesantren Ngroto Gubug diminta pulang untuk mengambil dua pusaka Sunan Kalijaga yang saat itu disimpan di atas Masjid Agung Demak.
Abdul Kadir dijemput menggunakan kereta kuda untuk pulang ke Demak untuk melaksanakan tugas. Setelah tugas mengambil dua pusaka peninggalan Sunan Kalijaga dapat dilaksanakan dengan baik maka Abdul Kadir kembali ke pondok.
Tak berapa lama kemudian, ontran-ontran rebutan pimpinan di Kadilangu berhasil reda setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 16, tertanggal 5 Mei 1883, tentang Pengangkatan Raden Ngabei Notobroto menjadi Kepala Perdikan Kadilangu.
Pada tahun 1883 Mbah Abdul Kadir pulang ke Wonosalam untuk dikhitan. Pada saat dikhitan dan belum sembuh ikut saudaranya menggembala ternak bebek di sekitaran stasiun Demak, tiba-tiba terjadi letusan gunung Krakatau. Bebeknya terkubur abu vulkanik. Abdul Kadir kecil dicari bibinya dan ketemu di stasiun Demak kemudian diajak pulang.
Di Pesantren Ngroto Mbah Abdul Kadir belajar mendalami ilmu agama seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid (akidah), ilmu nahwu dan shorof, ilmu tafsir dan hadits.
Saat mondok di Ngroto Gubug satu hari Mbah Yai menerima tamu seorang sayyid (keturunan Rasulullah SAW) yang kebetulan buta (matanya tidak bisa melihat). Ketika sang sayyid mau jalan-jalan berdakwah keliling. Kemudian meminta agar santri dari Demak yang bernama Abdul Kadir untuk menuntun membantunya jalan dalam suatu kegiatan berdakwah. Namun saat menuntun jalan tidak boleh melangkahi bayangan sang sayyid.
Setelah mondok di Ngroto Gubug cukup lama hingga menjabat lurah pondok maka pada usia muda Mbah Abdul Kadir disuruh menikah tapi belum mau kemudian boyongan dari pondok Ngroto Gubug pulang ke rumah.
Berguru Kepada Mbah Hadi di Girikusumo
Tidak lama di rumah Mbah Abduk Kadir kemudian berangkat ke pesantren Girikusumo Banyumeneng Mranggen Demak untuk berguru kepada KH Muhammad Hadi (Mbah Hadi).
Di pesantren Girikusumo Banyumeneng Mranggen beliau merasa senang hingga bertahan lumayan lama. Di pesantren Girikusumo Mbah Abdul Kadir mengajak keponakanya, Mbah Madrani.
Saat itu Mbah Abdul Kadir bersama Mbah Madrani ketika berangkat mengaji/berguru di Pesantren Girikusuma Mranggen yang diasuh KH. Muhammad Hadi (Mbah Hadi) seringnya naik kuda.
Raden Sastrohamijoyo Wafat
Tak berselang lama Raden Sastrohamijoyo yang sudah sepuh sakit kemudian wafat sekitar tahun 1890-an dalam usia 80-an tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman tidak jauh dari rumahnya yang berada di tepi Sungai Tuntang di Desa Wonosalam perbatasan dengan Desa Ploso.
Sungai Tuntang merupakan salah satu sungai bersejarah yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Demak. Sungai Tuntang berasal dari mata air Gunung Merbabu mengalir di sebelah selatan Gunung Ungaran menuju ke Demak dan bermuara di Laut Jawa.
Sungai Tuntang dahulu memiliki lebar 30 meter yang dapat di lewati oleh kapal-kapal dagang besar dari seluruh penjuru dunia. Pada zaman kolonial Belanda, Sungai Tuntang sering meluap, sehingga wilayah perkotaan Demak di kawasan Pendopo Bupati Demak sering kebanjiran.
Karenanya, dibangunlah tanggul di daerah Ploso, Kecamatan Wonosalam, sehingga aliran Sungai Tuntang membelok ke Kecamatan Bonang melalui Kalikondang, kemudian dialirkan ke laut. Dengan memindahkan aliran tersebut, sekarang Kota Demak tidak pernah banjir lagi.
Lokasi makam Raden Sastrohamijoyo yang semula di dekat Sungai Tuntang ikut terkena dampak proyek Pemerintah Hindia Belanda yang membuat jalur Sungai Tuntang Baru yang lurus ke arah Kalikondang dan Bonang.
Sungai Tuntang yang ada di sepanjang perkotaan Demak dinamakan “Kali Tuntang Lama” karena alirannya mati dan terjadi sedimentasi. Sungai itu akhirnya menjadi daratan dan hanya tersisa 6-7 meter yang saat ini digunakan sebagai aliran drainase dari warga sekitar.
Cerita yang berkembang di keluarga, menurut Eko Wisnu Atmojo, pada saat pencangkulan tanah untuk membuat jalur sodetan Sungai Tuntang Baru petugas yang mencangkul terasa sakit-sakitan. Kemudian didatangkan seorang ahli spiritual untuk melakukan “penerawangaan dan kontak batin”. Hasilnya ahli yang bersangkutan melihat sosok laki-laki tua namanya Eyang Raden Sastrohamijoyo berpakaian Jawa sedang duduk menghadap arah barat di pinggang belakang ada keris sambil memegang tasbih seolah sedang berzikir. Kemudian memberi isyarat agar yang mengambil tanah sengker adalah ahli warisnya atau keluarganya yaitu Abdul Kadir dan diiring untuk dimakamkan ulang di makam umum Wonosalam. Setelah dimakamkan diberi tetenger oleh pegawai Belanda berupa batu. Namun tetengernya kemudian sumingkir alias hilang. Lokasi makam yang disengker itu berada di pojok timur laut pemakaman umum Wonosalam yang sekarang persis di sebelah jalan tol.
Berwirausaha
Usai mondok di Girikusumo Mbah Abdul Kadir ingin belajar berwirausaha sekaligus untuk belajar dunia kehidupan nyata dan bergaul dengan bayak orang.
Beliau belajar di daerah Tugu Sayung tentang tata cara membuat kerajinan emas seperti anting-anting, kalung, gelang dan cincin juga menerima servise jika gelang atau anting-anting yang patah. Untuk itu beliau membeli sejumlah peralatan untuk bisa membuat kerajinan emas. Profesi ini sangat langka waktu itu dan hanya bisa dijalani oleh orang-orang tertentu apalagi biaya membeli peralatan emas mahal.
Setelah mampu membuat kerajinan emas dan membeli peralatannya Mbah Abdul Kadir mulai praktek membuat emas dan mengembara menjadi kemasan, yaitu profesi berjualan emas keliling (saat itu mata pencarian masih sulit, masih zaman penjajahan Belanda dan hidup rakyat masih menderita).
Dalam pengembaraannya jualan emas keliling sampailah di banyak tempat dan berkenalan dengan banyak orang. Hingga akhirnya hatinya jatuh cinta kepada gadis asal Dukuh Gading Desa Candisari Kecamatan Mranggen.
Membina Rumah Tangga
Pada tahun 1900-an, saat Mbah Abdul Kadir menikah dengan Mbah Salipah binti Abdurrohman yang menikah dengan Mbah Mainah anak Mbah Tong Singo (Lurah Desa Jetis tak jauh dari Candisari) yang besanan dengan Waliyullah Syekh Abdurrahman Subhi atau Mbah Subuh yang makamnya berada di Alas Roban Batang.
Di Dukuh Gading, Mbah Abdul Kadir menikah dua kali. Mbah Abdul Kadir dan istri pertamanya Mbah Salipah berdomisili di Dukuh Gading Desa Candisari. Hasil pernikahan pertama melahirkan Saleman (lahir 1911).
Setelah istri pertama wafat, Mbah Abdul Kadir menikah lagi dengan Kardimah binti Muden Kardi dan Sagimah Binti Mbah Abdurrohman bin Mbah Subuh Batang. Jadi istri kedua masih keponakan istri pertama.
Hasil pernikahan dengan istri kedua mempunyai empat anak yaitu Saikun (lahir 1926 wafat tahun 1963 dalam usia 37 tahun), Sukri (lahir 1929 wafat 2012 dalam usia 83), Matrohkatun Prayitno (lahir 1932 wafat 2008 dalam usia 76), Mat Sahid (lahir 1943-sekarang)
Ikut Berdakwah
Walau sudah menikah tetapi hubungannya dengan gurunya Mbah Muhammad Hadi (Girikusumo) masih terjalin baik sehingga secara berkala pada hari-hari tertentu masih berangkat mengaji ke Girikusumo.
Kondisi masyarakat Candisari saat itu Islamnya belum kuat, masih banyak yang abangan bahkan banyak yang non muslim. Penguasa setempat meminta Mbah Hadi untuk membantu syiar Islam di Candisari.
Mendengar permohonan tokoh masyarakat Desa Candisari untuk memperhatikan syiar Islam di Candisari maka Mbah Hadi Girikusumo meminta Mbah Abu Mi’roj untuk membuka pemukiman di daerah utara Candisari Mranggen. Mbah Abu Mi’roj adalah cucu menantu Mbah Hadi Girikusumo (menantu Mbah Ghofur, putera Mbah Hadi).
Setelah mendapatkan tanah dari penguasa setempat yang pedulli dengan syiar Islam di Desa Candisari maka dibukalah pemukiman baru di sisi utara Candisari tepatnya di Dukuh Gading. Mbah Abdul Kadir pun ikut membantu Mbah Abu Mi’roj dalam berdakwah di Desa Candisari Kecamatan Mranggen.
Program utama adalah bagaimana dapat mendirikan sebuah masjid sebagai pusat dakwah Islam. Masjid berfungsi sebagai tempat shalat, belajar agama, hingga melayani umat.
Setelah mendapatkan tanah untuk lokasi pembangunan masjid tersebut maka dimulailah pembangunan masjid. Masjid Gading berhasil dibangun pada tahun 1912.
Serambi masjid pertama itu adalah pendopo rumah Mbah Abdul Kadir. Mbah Abdul Kadir kemudian ikut aktif dalam syiar Islam di Gading dengan suaranya yang merdu kemudian menjadi muadzin di Masjid Gading.
Dalam perkembangannya Dukuh Gading berubah menjadi kampung santri dan tumbuh banyak pondok pesantren dan lembaga pendidikan.
Ikhlas dan Merakyat
Mbah Abdul Kadir memiliki kepribadian yang ikhlas dan merakyat. Walau lahir dari keluarga priyayi namun tidak membuatnya angkuh dan sombong. Bahkan beliau lebih nyaman menjadi rakyat biasa yang hidup di desa dan istiqomah mengikuti dawuh gurunya.
Beliau memiliki tanah di Wonosalam dan Ploso warisan orang tuanya namun tidak semuanya dia ambil. Sebagian dijual untuk menjadi bekal hidup baru berumah tangga dan sebagian lagi diberikan kepada saudaranya.
Menurut cerita Eko Wisnu Atmojo, cucu Mbah Abdul Kadir, yang mendapatkan cerita tutur dari Mbah Kardimah (istri kedua Mbah Abdul Kadir), bahwa Mbah Abdul Kadir sebetulnya mendapatkan jatah warisan tanah dari ibunya yang anak lurah Ploso Wonosalam, tapi karena jauh tidak dapat mengelolanya, sehigga warisan tanah diserahkan kepada saudaranya di Ploso.
Berkat kerja kerasnya Mbah Abdul Kadir yang sudah berdomisili di Dukuh Gading akhirnya memiliki tanah yang luas baik sawah maupun pekarangan yang diwariskan yang dikelola dengan baik.
Beliau menghabiskan hidupnya dengan bertani dan menjadi kemasan yaitu orang yang ahli dibidang kerajinan emas, sambil ikut berdakwah dan berdagang di pasar.
Wafat dan Fenomena “Makam Unthuk”
Mbah Abdul Kadir wafat di Dukuh Gading Desa Candisari Kecamatan Mranggen Demak tanggal 21 November tahun 1947 pada hari Jum’at Pahing dalam usia 76 tahun. Makamnya di belakang MTs Negeri 1 Mranggen di dukuh Gading desa Candisari Mranggen Demak.
Salah satu fenomena yang unik dan langka di makam Mbah Abdul Kadir adalah adanya “tanah unthuk” di atas pusara makam beliau. Fenomena ini tentu tidak lazim. Tinggi “tanah unthuk” kisaran satu setengah meter hampir sampai atap cungkup makam. Menurut penuturan orang-orang tua dahulu jika ada makam yang terdapat “tanah unthuk” menandakan kalau itu makam milik orang shaleh dan berbudi pekerti yang luhur. []